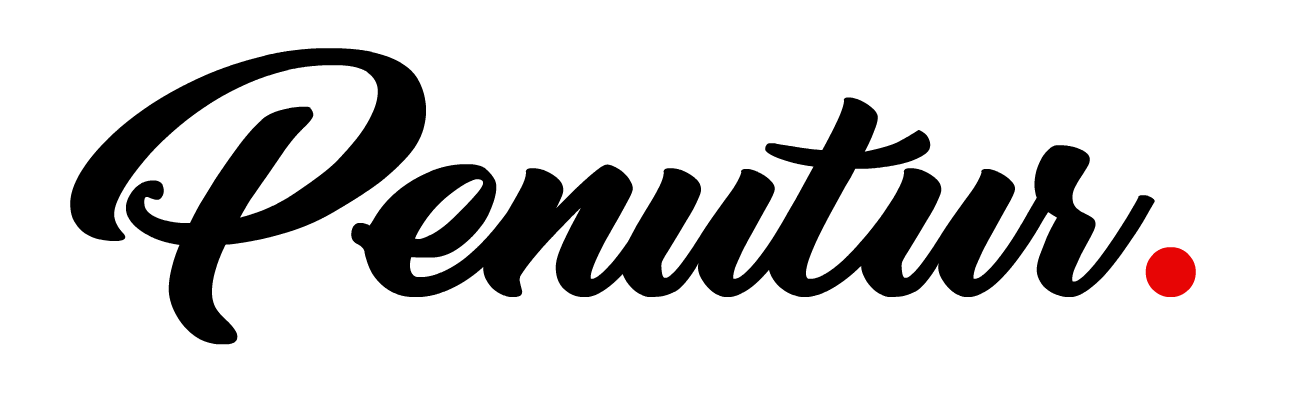Hadiah Nobel Perdamaian: Topeng Politik Barat Menipu Dunia
Share

PENUTUR.COM – Setiap tahun, Komite Nobel Perdamaian di Norwegia mengumumkan pemenang yang disebut-sebut mewakili “semangat perdamaian dunia.” Namun, setiap tahun pula muncul pertanyaan lama: perdamaian versi siapa?
Ketika María Corina Machado diumumkan sebagai penerima Nobel Perdamaian 2025, banyak pihak di Venezuela dan Dunia Selatan langsung membaca pesan politik di baliknya—bukan pesan kemanusiaan, melainkan geopolitik.
Machado dan Jejak Kepentingan Amerika Serikat–Israel di Venezuela
Machado bukan sekadar oposisi terhadap Nicolás Maduro; ia adalah simbol perpanjangan tangan kepentingan Washington di Caracas. Sejak awal 2000-an, ia dikenal sebagai penerima dukungan dari National Endowment for Democracy (NED), lembaga yang didanai Kongres AS dan lama dikritik karena membiayai proyek-proyek perubahan rezim di Amerika Latin (Washington Post, 2014).
Machado juga secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Israel.
Pada Juli 2020, partai Vente Venezuela yang dipimpinnya menandatangani perjanjian kerjasama dengan Partai Likud, Israel, yang dipimpin Netanyahu.
Sebelum itu, bahkan mengirim surat kepada Netanyahu pada 2018 meminta Israel menggunakan kekuatan dan pengaruhnya (termasuk intervensi militer) untuk menaklukkan rezim Venezuela.
Dalam wawancara 2021, ia menyebut “Israel adalah sekutu alami Venezuela yang merdeka” dan berjanji memindahkan kedutaan besar Venezuela dari Tel Aviv ke Yerusalem bila ia berkuasa—langkah yang hanya diambil oleh pemerintahan yang sangat pro-Zionis seperti AS di bawah Donald Trump. Demikian menurut wawancaranya di Times of Israel pada 2021.
Dengan posisi itu, kemenangan Machado di Nobel Perdamaian 2025 segera dibaca bukan sebagai pengakuan atas perjuangan rakyat Venezuela, melainkan sebagai endorsemen politik terhadap kubu pro-AS dan pro-Israel. Maduro sendiri menyebutnya “penghargaan imperialis yang dibungkus kata perdamaian”.
Secara lugas, pada 10 Oktober, di X, Machado mempersembahkan Nobel Perdamaian 2025-nya kepada Donald Trump atas “dukungan” Trump terhadap perjuangannya melawan rezim Maduro di Venezuela.
Nominasi oleh Politisi “Lobi Israel” di Washington
Keterkaitan itu makin jelas jika menelusuri siapa yang menominasikan Machado untuk Nobel. Bocoran media Norwegia menunjukkan nama-nama seperti Marco Rubio, Rick Scott, dan Michael Waltz—semuanya politisi Partai Republik dari Florida, negara bagian dengan kepentingan kuat terhadap kebijakan Amerika Latin dan hubungan dekat dengan lobi Israel (Politico, 2025).
Rubio sendiri dikenal sebagai “politisi pro-Israel garis keras.” Laporan OpenSecrets.org mencatat bahwa sejak 2010 ia telah menerima lebih dari 1 juta dolar AS dari kelompok donatur yang berafiliasi dengan AIPAC (American Israel Public Affairs Committee).
Ia bahkan disebut “murid politik” mendiang miliarder Zionis Sheldon Adelson, yang mendanai kampanye presiden Rubio pada 2016 (Haaretz, 2016).
Rubio lebih tepat disebut sebagai politisi dengan prinsip “Israel First” daripada “American First” yang menjadi propaganda pemerintahan Trump.
Seperti halnya Rubio, politisi pendukung Machado lainnya adalah politisi “Israel First”. Senator Rick Scott juga tercatat menerima sekitar $657 ribu dari jaringan donatur pro-Israel, sementara Waltz mendapat $246 ribu (OpenSecrets, 2024).
Dengan kata lain, nominasi Machado datang dari lingkaran politisi yang dibiayai oleh kelompok kepentingan Israel dan berfokus pada kebijakan intervensi di Amerika Latin.
Demokrasi dan HAM: Topeng Barat yang Brutal
Machado memenangkan Nobel dengan alasan “memperjuangkan demokrasi di Venezuela.” Namun, definisi “demokrasi” yang digunakan Komite Nobel jelas berpihak pada tafsir liberal Barat—sebuah mitos yang menutupi fakta bahwa negara-negara pendukungnya justru menjadi pelaku utama kekerasan global.
Amerika Serikat, sang penjaga moral dunia, telah berkali-kali menggunakan narasi “demokrasi” dan “hak asasi manusia” untuk membenarkan intervensi militer yang menghancurkan bangsa lain.
Invasi ke Irak tahun 2003, dilakukan tanpa dasar hukum dan tanpa mandat PBB, menewaskan lebih dari 500.000 warga sipil (Iraq Body Count, UN, 2023).
Serangan terhadap Libya tahun 2011—yang diklaim demi “melindungi rakyat dari tirani”—menghancurkan negara paling makmur di Afrika, menjadikannya ladang perang dan perdagangan budak modern ( Human Rights Watch, 2016; UNHCR, 2022).
Di Suriah, AS dan sekutunya mendanai berbagai kelompok bersenjata dengan dalih “membantu oposisi,” tetapi hasilnya adalah perang proksi yang memicu lebih dari 6,8 juta pengungsi ( UNHCR, Report on Displacement 2023). Semua itu dilakukan atas nama demokrasi—kata suci yang berubah menjadi lisensi untuk membunuh.
Ironisnya, negara yang mengaku sebagai pelindung hak asasi manusia itu kini menjadi sponsor utama genosida di Gaza. Sejak Oktober 2023 hingga Oktober 2025, lebih dari 67.000 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak ( UN OCHA, 2025; Al Jazeera, 2025).
Sementara dunia memprotes, Washington terus memasok bom 30.000 pon kepada Israel dan berulang kali memveto resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB.
Dalam konteks itu, pemberian Nobel kepada María Corina Machado—seorang politisi yang secara terbuka mendukung Israel—terasa seperti ironi pahit. Bagaimana mungkin seseorang yang mendukung rezim pendudukan di Palestina disebut “pembawa perdamaian”?
Namun ironi ini menjadi masuk akal bila dilihat dari sisi lain: politik minyak dan ekonomi perang.
Venezuela bukan negara kecil tanpa arti; ia memiliki cadangan minyak terbesar di dunia—sekitar 303 miliar barel, melebihi Arab Saudi (sumber: OPEC Annual Statistical Bulletin 2024).
Cadangan itu menjadi tulang punggung geopolitik dunia energi. AS, yang selama satu abad bergantung pada minyak Timur Tengah, tentu melihat Venezuela sebagai aset strategis yang “salah pemilik.”
Sanksi ekonomi dan upaya delegitimasi terhadap pemerintahan Caracas bukanlah karena “otoritarianisme,” tetapi karena Venezuela menolak menyerahkan kendali minyaknya kepada korporasi Barat.
Sementara Machado merupakan pendukung kapitalisme dan privatitsasi minyak Venezuela. Itulah sebabnya setiap tokoh oposisi yang pro-liberalisasi—seperti Machado—langsung dipuji oleh Washington, Bank Dunia, dan media Barat sebagai “simbol kebebasan.”
Dalam skema ini, penghargaan Nobel menjadi bagian dari ritual legitimasi politik global. Ia bukan sekadar medali, tapi juga pesan: siapa pun yang sejalan dengan kepentingan geopolitik AS akan dipuja sebagai pahlawan demokrasi, sementara yang melawan akan dicap diktator, teroris, atau ancaman bagi perdamaian dunia.
Begitulah cara “demokrasi” dan “HAM” bekerja dalam dunia yang dikendalikan oleh kekuasaan modal dan senjata. Ia bukan nilai universal, melainkan topeng moral bagi kekerasan yang disponsori negara.
Netralitas Komite Nobel: Mitos yang Sudah Lama Runtuh
Komite Nobel kerap menampilkan diri sebagai penjaga moral dunia, pemberi penghargaan bagi tokoh yang dianggap memperjuangkan perdamaian. Namun sejarah menunjukkan: “netralitas” mereka lebih menyerupai ilusi diplomatik daripada sikap etis.
Lihat saja tahun 2009, ketika Barack Obama, presiden Amerika Serikat yang baru menjabat sembilan bulan, dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian — bukan karena pencapaian, melainkan karena “harapan.”
Saat itu, Komite Nobel menyatakan bahwa Obama “membawa visi dunia tanpa senjata nuklir.” Ironisnya, pada tahun yang sama, ia menandatangani perluasan operasi militer ke Afghanistan dan memerintahkan gelombang pertama 33.000 tentara tambahan ke sana (CSIS, UNAMA 2009).
Alih-alih mengakhiri perang seperti janjinya, Obama justru memperluas perang setidaknya ke tujuh negara — Afghanistan, Iraq, Pakistan, Yaman, Somalia, Libya, dan Suriah.
Menurut data CNN (2017), AS menjatuhkan lebih dari 26.000 bom hanya dalam tahun 2016 saja. Laporan Bureau of Investigative Journalism menyebutkan bahwa di bawah pemerintahan Obama, serangan drone meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dibanding era Bush, dengan 542 serangan yang menewaskan sekitar 3.797 orang, termasuk 324 warga sipil (Bureau of Investigative Journalism, 2017).
Laporan proyek Costs of War dari Brown University memperkirakan bahwa kebijakan militer AS selama periode 2009–2017 berkontribusi pada 800.000 hingga 1 juta kematian langsung dan tidak langsung akibat konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara — belum termasuk jutaan pengungsi dan runtuhnya stabilitas politik di wilayah tersebut.
Di Pakistan dan Yaman, diterapkan kebijakan drone “presumptif” berarti siapa pun yang berada dalam radius serangan dianggap kombatan kecuali terbukti sebaliknya.
Hasilnya: ribuan korban sipil tanpa proses hukum (Bureau of Investigative Journalism, 2016). Bahkan PBB mengecam metode itu sebagai bentuk “extrajudicial execution.”
Sementara itu di Libya, intervensi NATO yang dipimpin AS tahun 2011 — diklaim untuk “melindungi warga sipil” — justru menggulingkan pemerintahan Gaddafi dan memicu perang sipil berkepanjangan yang menewaskan lebih dari 50.000 orang (UN, HRW, 2016).
Negara itu kini terpecah, menjadi pasar senjata dan jalur utama perdagangan manusia menuju Eropa.
Apakah semua ini tampak seperti karya seorang “peraih Nobel Perdamaian”?
Namun Komite Nobel tidak berhenti di situ. Tahun 1994, mereka memberikan penghargaan yang sama kepada Shimon Peres, arsitek militer Israel yang bertanggung jawab atas kebijakan nuklir rahasia dan pendudukan militer Palestina.
Saat menjabat Menteri Pertahanan, Peres mengawasi operasi militer besar di Lebanon tahun 1996 — termasuk pembantaian Qana, ketika artileri Israel menewaskan lebih dari 100 warga sipil yang berlindung di markas PBB (Human Rights Watch, 1996).
Peres memang menandatangani perjanjian Oslo, tetapi ia juga menyetujui pembangunan pemukiman baru di tanah Palestina beberapa bulan setelah menerima Nobel.
Dalam kata-kata Edward Said, seorang intelektual Palestina: “Hadiah Nobel itu bukan untuk perdamaian, melainkan untuk legitimasi penaklukan.”
Dari Obama hingga Peres, pola yang sama muncul: Komite Nobel memberi penghargaan bukan kepada korban perang, tapi kepada mereka yang memiliki kekuasaan menentukan siapa yang berhak hidup dan mati — selama mereka berbicara dengan aksen Barat.
Kisah-kisah ini membongkar wajah sebenarnya dari politik Nobel: sebuah lembaga yang mengukuhkan hegemoninya sendiri di bawah topeng “perdamaian universal.” Ia tidak netral; ia hanya berpihak pada tatanan dunia yang diatur oleh NATO dan Washington.
Jadi ketika Komite Nobel menominasikan figur seperti María Corina Machado, seorang politisi sayap kanan yang disokong oleh senator AS pro-Israel seperti Marco Rubio, publik sepatutnya bertanya: Apakah ini soal “perdamaian dan demokrasi,” atau sekadar bab baru dalam diplomasi simbolik yang menjustifikasi intervensi politik atas nama moralitas?
Nominasi Trump, Netanyahu, dan Daniella Weiss: Potret Dominasi Zionisme
Tahun 2025, daftar kandidat Nobel Perdamaian memuat 338 nama. Di antaranya—dan ini penting—terdapat Donald Trump, Benjamin Netanyahu, dan Daniella Weiss, tokoh-tokoh yang justru dianggap simbol perang dan pendudukan (BBC, 2025).
Trump dinominasikan oleh anggota Kongres Partai Republik seperti Buddy Carter dan Claudia Tenney atas perannya dalam “gencatan senjata Gaza”—padahal di lapangan, bom buatan AS masih menghujani wilayah itu (Al Jazeera, 2025).
Netanyahu, yang tengah menghadapi arrest warrant dari ICC atas tuduhan genosida dan kejahatan perang di Gaza (2024), bahkan sempat disebut “layak Nobel” oleh think tank sayap kanan American Enterprise Institute (AP News, 2024).
Lebih absurd lagi, Daniella Weiss—aktivis ekstremis Israel yang menyerukan pengusiran total warga Arab dari Tepi Barat dan Gaza—juga masuk daftar nominasi lewat dua profesor dari Ariel dan Ben-Gurion University (Arab News, 2025).
Weiss memimpin gerakan Nachala, kelompok pemukim yang telah dikenai sanksi oleh Kanada dan Inggris karena kekerasan terhadap warga Palestina (Reuters, 2024).
Jika tokoh-tokoh seperti itu dapat dinominasikan untuk Hadiah Perdamaian, maka kita pantas bertanya: apa arti “perdamaian” bagi Komite Nobel?
Kritikus seperti Noam Chomsky dan Tariq Ali sudah lama menyebut Nobel Perdamaian sebagai “penghargaan yang berubah fungsi menjadi alat legitimasi moral kekuasaan global Barat.”
Ia bukan lagi perayaan kemanusiaan universal, melainkan instrumen untuk menentukan siapa yang dianggap sah berbicara atas nama perdamaian.
Dengan memberikan penghargaan kepada Machado, Komite Nobel secara tidak langsung meneguhkan narasi bahwa perubahan politik yang didukung AS adalah perjuangan moral, sedangkan perlawanan terhadap dominasi Barat adalah ekstremisme.
Padahal, rakyat Venezuela berjuang bukan hanya melawan diktator, tetapi juga melawan blokade ekonomi yang diperpanjang oleh Washington selama dua dekade. Jika “perdamaian” berarti tunduk pada struktur kekuasaan global, maka istilah itu kehilangan maknanya.
Hadiah Nobel Perdamaian seharusnya menjadi simbol universal dari rekonsiliasi dan kemanusiaan. Namun sejarah menunjukkan bahwa ia kerap berfungsi sebagai alat politik yang menyamarkan kepentingan hegemonik Barat.
Cermin Kemunafikan dan Penipuan ala Barat
Machado hanyalah bab terbaru dari kisah panjang itu—dari Kissinger hingga Obama, dari Peres hingga Machado—semua menegaskan satu pola: bahwa “perdamaian” dalam kamus Nobel berarti perdamaian yang sesuai dengan kepentingan Washington dan Tel Aviv.
Hadiah Nobel Perdamaian, dalam praktiknya, telah menjadi upaya pencucian moral Barat—sebuah mekanisme whitewashing yang menutupi kekerasan struktural dan hipokrisi politik global. Ia berfungsi layaknya topeng kemanusiaan bagi peradaban yang sesungguhnya tidak demokratis dan tidak humanis, yang memproduksi perang sekaligus mengklaim diri sebagai penjaga damai.
Nobel bukan lagi penghargaan untuk perdamaian, melainkan ritual kepuasan moral Barat: sebuah bentuk autoerotisme politik jika istilah “masturbasi politik” dianggap terlalu vulgar di mana kekuatan imperium memuji dirinya sendiri atas penderitaan yang diciptakannya.
Setiap medali emas yang diserahkan di Oslo bukanlah lambang kemuliaan, melainkan cermin narsistik yang memantulkan wajah palsu dunia yang mereka ciptakan—dunia di mana bom dijatuhkan atas nama kebebasan, dan embargo dijustifikasi atas nama HAM.
Selama definisi “perdamaian” dan “demokrasi” tetap dimonopoli oleh kekuatan yang membiayai perang dan penjajahan, maka setiap piala Nobel hanyalah simbol kosong—kilau yang menutupi darah dan air mata yang terus mengalir di Gaza, Caracas, Baghdad, dan Tripoli.
Kini dunia Selatan sudah tidak buta. Mereka melihat bahwa di balik bahasa kemanusiaan yang manis, ada mesin kekuasaan yang haus kendali.
Dan selama Komite Nobel tetap menjadi corong nilai-nilai imperium itu, maka “perdamaian” versi mereka tak lebih dari mimpi palsu dalam bingkai emas—hadiah untuk diri mereka sendiri atas keberhasilan menipu umat manusia.